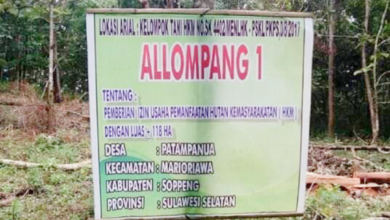Rutan Kelas IIB Jeneponto Gelar Apel Pagi

Jeneponto, Jurnalsepernas.id – APEL pagi yang dirangkaikan dengan penyematan tanda pangkat kepada 15 orang petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto, Sulawesi Selatan Sulsel), Senin, (08/08) dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas IIB Jeneponto, Hendrik.
Sebanyak 15 orang pegawai Rutan Kelas IIB Jeneponto disematkan tanda pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya oleh Kepala Rutan Kelas IIB Jeneponto.

Hendrik, Kepala Rutan Kelas IIB Jeneponto sekaligus selaku pembina apel memberikan ucapan selamat dan sukses kepada 15 orang pegawai Rutan Kelas IIB Jeneponto atas kenaikan pangkatnya sekaligus dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja yang telah ditunjukkan serta memberikan banyak sumbangsih baik itu tenaga, pikiran bahkan waktu kepada institusi khususnya di Rutan Kelas IIB Jeneponto.
Pada kesempatan itu, Hendrik mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan menyemarakkan Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM-RI) Hari Dharma Karya Dhika Ke-77.

Diakhir amanatnya, Hendrik menghimbau kepada seluruh petugas peserta apel pagi untuk tetap menjaga kekompakan, integritas, dan selalu memberikan yang terbaik untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya untuk Rutan Jeneponto. (Sumber: Humas Rutan Jeneponto).
Pewarta: Jamaluddin
Editor : Loh